Penulis : Sri Radjasa
Pemerhati Intelijen
Dalam setiap negara modern, kemampuan presiden untuk mendengar denyut rakyatnya adalah fondasi legitimasi. Namun dalam beberapa bulan terakhir, publik menyaksikan gejala mengkhawatirkan: informasi strategis mengenai bencana dan keamanan nasional terlambat tiba di meja Presiden Prabowo. Bencana di Sumatera dan Aceh yang merenggut banyak korban jiwa, kerusuhan besar Agustus 2025, hingga polemik laporan palsu soal pemulihan listrik di Aceh memperlihatkan pola yang sama, dimana presiden selalu datang terlambat, bukan karena enggan bertindak, melainkan karena negara gagal memberinya gambaran yang benar.
Fenomena ini oleh publik Aceh dan Sumatera disebut sebagai “virus budeg” di Istana, metafora keras bahwa pusat kekuasaan kehilangan kepekaan terhadap realitas. Dalam perspektif intelijen, problem ini jauh lebih serius daripada sekadar miskomunikasi. Ini mengarah pada kerusakan sistemik dalam governance of information, sebuah kondisi yang pernah memicu tumbangnya banyak pemerintahan di negara berkembang. Ketika arus informasi tersumbat, negara menjadi lamban, kabur, dan buta terhadap ancaman.
Jika kita membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai tebal komunikasi Istana, serta apa yang harus dilakukan Presiden agar tidak menjadi pemimpin yang berjalan dalam gelap di tengah bangsa yang sedang berduka.
Bencana Informasi yang Lebih Berbahaya dari Bencana Alam
Dalam penanganan bencana Aceh dan Sumatera, publik dibuat terkejut oleh pernyataan seorang pejabat BNPB yang menyebut bahwa bencana itu “tidak besar, hanya media sosial yang membesar-besarkan”. Kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, dimana kerusakan meluas, korban jiwa meningkat, jaringan listrik dan telekomunikasi runtuh, dan ribuan warga mengungsi dalam situasi serba minim. Bahkan pemerintah Aceh menyebut kerusakan fisiknya jauh lebih masif daripada perkiraan awal.
Lebih mengkhawatirkan, pernyataan pejabat itu disampaikan pada saat Presiden masih bergantung pada laporan resmi yang masuk melalui rantai komando negara. Artinya, informasi yang diterima Presiden pada jam-jam kritis itu sudah terdistorsi.
Ketika kemudian Presiden bereaksi terlambat, publik mengira ia tidak peduli. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah information failure pada tingkat paling fundamental.
Fenomena serupa telah muncul sebelumnya. Kerusuhan besar Agustus 2025 berkembang cepat menjadi ancaman destabilisasi nasional. Namun Presiden tampak lambat merespons. Laporan-laporan intelijen dan keamanan mengenai potensi eskalasi ternyata bergerak tersendat di lapisan birokrasi, sehingga ketika Presiden menerima laporan lengkap, massa sudah berkumpul, dan situasi meluas ke berbagai daerah.
Dugaan sementara dari kalangan analis tata-pemerintahan menyebutkan bahwa Istana mengalami over-filtering—proses penyaringan informasi yang terlalu ketat oleh lingkar dalam Presiden. Penyaringan ini mungkin dimaksudkan untuk meredam reaksi impulsif Presiden terhadap isu sensitif. Namun dalam manajemen krisis, menyaring terlalu banyak justru fatal. Informasi yang penting tetapi tampak “kasar”, “belum final”, atau “terlalu sensitif” sering kali justru menjadi alarm paling awal bagi pemerintah untuk bertindak cepat.
Puncak ironi terjadi ketika seorang menteri senior mengumumkan bahwa pemulihan listrik Aceh telah mencapai 93 persen, dan Kepala BNPB menyatakan 100 persen “clear”. Faktanya: sebagian masyarakat Aceh masih hidup dalam gelap, komunikasi terputus, dan fasilitas publik berkali-kali gagal berfungsi. Jika angka-angka yang dilaporkan kepada Presiden bersumber dari laporan yang sama, maka jelas ada kegagalan struktural yang harus diselidiki.
Di titik ini, krisis yang dihadapi negara bukan semata bencana alam, melainkan bencana informasi.
Kegagalan Sistemik yang Lahir dari Warisan Politik dan Kultur Kekuasaan
Mengapa informasi bisa tersumbat semacam itu? Dari perspektif intelijen politik, ada tiga pola yang terlihat jelas.
Pertama adalah faktor struktural. Sekretaris Kabinet berperan sebagai gerbang utama informasi yang masuk ke ruang keputusan presiden. Namun bila gerbang itu dikendalikan oleh figur yang cenderung terlalu selektif, minim pengalaman lapangan, atau memiliki preferensi politik tertentu, maka informasi yang masuk ke Presiden menjadi sangat bergantung pada subjektivitas personal. Dalam praktik pemerintahan manapun, subjektivitas semacam ini adalah musuh bagi objektivitas negara.
Kedua adalah kultur komunikasi satu arah yang selama bertahun-tahun tumbuh subur. Lingkar Istana cenderung memberi laporan yang “menenteramkan”, bukan laporan yang menggambarkan kebenaran mentah. Para pejabat di bawah enggan menyampaikan kabar buruk karena takut dianggap tidak kompeten. Ini adalah pola klasik bureaucratic self-censorship yang sering terjadi di negara-negara dengan kepemimpinan kuat. Presiden terkurung dalam ruang gema (echo chamber) yang hanya menghadirkan narasi positif.
Ketiga, dan inilah yang paling rumit, adalah dinamika warisan politik. Banyak institusi strategis masih diisi oleh orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan kekuasaan era sebelumnya. Mereka tidak selalu berniat buruk, tetapi keberadaan kepentingan politik, loyalitas lama, dan patronase yang belum sepenuhnya terputus membuat arus informasi rentan dipolitisasi. Dalam situasi ekstrem, bisa saja ada pihak yang mengambil keuntungan dari membiarkan Presiden terlihat salah langkah atau terinformasi keliru.
Dalam literatur intelligence governance, kondisi seperti ini disebut internal obstruction, yakni sabotase halus terhadap aliran informasi, tanpa harus melakukan tindakan ilegal. Cukup dengan menunda laporan beberapa jam, membuang detail penting, atau menyajikan data yang terpotong, sehingga seorang presiden dapat dibuat terlihat tidak kompeten di hadapan publik.
Di tengah bencana Aceh dan Sumatera, pola ini tampak terlalu jelas untuk diabaikan.
Radical Break: Satu-satunya Jalan Mengembalikan Pendengaran Negara
Pemerintahan Prabowo baru memasuki fase awal, namun ujian yang datang bertubi-tubi telah memperlihatkan sesuatu yang penting: struktur komunikasi Istana tidak siap menghadapi negara sebesar Indonesia dalam keadaan krisis beruntun. Karena itu, Presiden membutuhkan langkah besar yang tidak biasa, yaitu sebuah radical break.
Pertama, Presiden harus segera merombak rantai komunikasi strategis di Istana. Screening informasi tidak boleh digenggam oleh satu-dua figur saja. Presiden membutuhkan sistem multi-channel intelligence yang membuka jalur langsung dari BNPB, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Badan Intelijen, hingga lembaga-lembaga teknis. Banyak presiden di negara maju melakukan ini untuk menghindari penyempitan informasi di tingkat staf.
Kedua, Presiden harus mengevaluasi kembali posisi para menteri atau pejabat kunci warisan pemerintahan sebelumnya. Bukan semata karena mereka adalah “eks siapa”, tetapi karena setiap pemerintahan membutuhkan kesetiaan pada visi baru, bukan loyalitas pada patron lama. Ketika pejabat strategis berada dalam dua orbit loyalitas, maka presiden mana pun akan berada dalam bahaya.
Ketiga, Presiden harus menuntut transparansi data di setiap kementerian. Kebiasaan menyajikan angka yang tampak sempurna tetapi tidak cocok dengan realitas lapangan harus dihentikan. Data yang salah adalah pengkhianatan tertinggi terhadap rakyat.
Keempat, Presiden harus membangun budaya baru: tidak menghukum pembawa kabar buruk. Dalam krisis, laporan buruk adalah bahan bakar keputusan tepat. Pemimpin yang hanya ingin mendengar hal-hal baik akan dikelilingi oleh pembohong profesional.
Pada akhirnya, masalah terbesar yang dihadapi negara ini bukan bencana alam, bukan kerusuhan, bukan listrik padam. Masalah terbesar kita adalah negara yang lambat mendengar suara rakyatnya sendiri. Ketika Istana kehilangan pendengaran, seluruh bangsa berada dalam bahaya.
Presiden adalah pemegang mandat tertinggi, tetapi mandat itu hanya dapat dijalankan bila negara mampu mengalirkan kebenaran apa adanya ke hadapannya. Tanpa itu, presiden akan berjalan tertatih di kegelapan, sementara rakyat menanggung akibat dari kebijakan yang lahir dari informasi yang rusak.
Saatnya Presiden memutus mata rantai kebudegan politik di Istana. Negara tidak boleh tuli ketika rakyatnya sedang berteriak meminta pertolongan.
EDITOR: REYNA
Related Posts

Ketegangan Internal Warnai Rencana Munaslub MES

PT. Platinum Cemerlang Indonesia Manipulasi Limbah B3 dan WNA Sebagai Tenaga Kerja, APH Setempat dan Polda Jatim Harus Bertindak Tegas

DPR Sentil Pemerintah: “Bantuan Triliunan Jangan Kalah Viral dari Donasi Swasta”

Jakarta Terbakar: Tragedi Ledakan dan Kebakaran di Gedung Kantor Kemayoran, 22 Meninggal

Debat Panas Soal “Scan Ijazah Asli”: Pengacara RRT Soroti Dugaan Pembohongan Publik dan Disparitas Penegakan Hukum

Untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat, Baznas Sumenep Bantu Modal Usaha UMKM Masalembu

Forensik Digital, Transparansi Publik, dan Ujian Integritas Ilmu

Pemburu Diburu Buruan

Banjir Besar: Alarm Krisis Tata Kelola Nasional

Bencana Itu: Siapa Penanggung Utama?

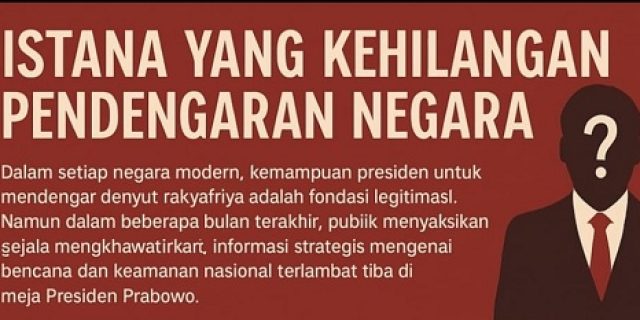


No Responses