Oleh: Radhar Tribaskoro
Penulis adalah Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air
Dalam percakapan whatsapp di suatu pagi yang tampak biasa, sebuah kabar beredar: kasus ijazah palsu itu akan dibawa ke ruang mediasi. Kata “mediasi” diulang, seperti mantra yang ingin menenangkan, seolah semua persoalan dapat diurai dengan keramahan, dengan senyum yang meredam silang sengketa. Tapi sesuatu terasa ganjil. Mediasi dilakukan ketika dua pihak punya versi kebenaran yang setara, atau ketika sebuah perselisihan murni teknis, murni administratif. Mediasi tidak diperuntukkan bagi kebenaran yang dicabut dari akarnya. Tidak untuk dusta yang merusak sendi moral sebuah republik. Karena pertanyaan pertama yang bangkit, sederhana saja: apa yang sebenarnya hendak dimediasi?
Sejak awal publik yang mendukung figur-figur seperti Roy, Rismon dan Tifa—orang-orang yang masih percaya integritas harus menjadi pondasi politik—tidak meminta banyak. Mereka tidak menuntut kesempurnaan. Mereka tidak memerlukan pemimpin yang suci tanpa cela. Yang mereka inginkan hanyalah pejabat yang tidak menganggap kebohongan sebagai teknik. Mereka ingin republik yang tidak dikendalikan oleh manipulasi kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi tradisi besar. Mereka ingin pemerintahan yang tidak menyembunyikan sesuatu dari rakyatnya. Pertanyaannya: bisakah nilai-nilai itu ditawar? Apakah kejujuran bisa dinegosiasikan di meja perundingan layaknya sengketa perdata?
Kasus ijazah palsu bukan semata arsip yang hilang, bukan kesalahan ketik yang diperbaiki di esok hari. Ia mengandung sesuatu yang jauh lebih dalam: sebuah riwayat dusta yang merembes pelan, lalu menetap. Ia bukan persoalan administratif—ia persoalan moral. Dan moral, sejak awal sejarah filsafat, tidak pernah menjadi wilayah tawar-menawar. Kita mungkin dapat menawar harga beras, menawar biaya proyek, menawar masa kampanye. Tapi menawar dusta berarti menawar fondasi yang mendirikan republik ini.
Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa kasus ijazah palsu itu, pada hakikatnya, menyentuh tekad bangsa untuk menegakkan etika anti-dusta. Ucapan itu, entah bagaimana, terdengar seperti gema lama dari tradisi yang lebih tua dari republik ini sendiri. Ia seperti pantulan dari ajaran para pujangga Jawa tentang kejujuran sebagai inti kepemimpinan. “Seorang pemimpin bukanlah ia yang serba tahu,” tulis Yasadipura, “melainkan ia yang tak membiarkan dirinya berdiri di atas dusta.” Ada nada getir dalam kata-kata itu ketika dibawa ke era kita sekarang—ketika dusta diperlakukan seperti kesalahan yang dapat diselesaikan dengan surat kuasa dan meja bundar.
Di negara modern, dusta bukan hanya persoalan karakter individu; ia adalah persoalan struktur. Kita terlalu sering membiarkan kebohongan tumbuh menjadi kebiasaan. Dari laporan keuangan yang dibengkokkan, dari angka statistik yang disulap, hingga ijazah yang tidak pernah ada tetapi dicatat seolah nyata. Dan setiap kali kita membiarkan satu dusta lewat tanpa konsekuensi, kita sedang menuliskan preseden: bahwa kebenaran dapat dimanipulasi, bahwa integritas dapat diatur besar kecilnya sesuai kebutuhan politik.
Apa yang disebut politik dusta itu tidak pernah sekadar tentang satu orang. Ia adalah proses menyeluruh yang melibatkan pembiaran. Ia memerlukan birokrasi yang enggan memeriksa. Ia membutuhkan partai politik yang menutup mata. Ia mengandalkan media yang letih, publik yang terlanjur pasrah, dan elit yang memutuskan bahwa stabilitas lebih penting daripada transparansi. Pada titik itu, dusta bukan lagi kejadian individual; ia menjadi ekosistem.
Banyak orang mungkin bertanya, mengapa urusan ijazah—sebuah hal yang tampak sederhana—harus membuat republik terguncang? Tetapi republik yang sehat menggantungkan masa depannya pada hal-hal sederhana semacam itu. Sebab dusta kecil yang dibiarkan tidak lagi kecil. Ia menjadi model. Ia menjadi template perilaku pejabat berikutnya. Republik kehilangan orientasinya ketika para pemimpinnya membiarkan kebohongan menjadi bagian dari prosedur. Ketika itu terjadi, mediasi tidak lagi menjadi proses mencari mufakat, melainkan cara halus untuk menyapu sesuatu ke bawah karpet.
Pada titik inilah publik bertanya: apakah mungkin sebuah negara berjalan tanpa integritas? Ada negara yang bertahan tanpa demokrasi, tanpa pasar bebas, bahkan tanpa oposisi. Tetapi tidak ada negara yang bertahan tanpa kepercayaan. Kepercayaan bukan institusi formal yang dapat dibentuk lewat UU. Ia lahir dari pengalaman publik bahwa pemimpinnya tidak akan menipu mereka. Ketika sebuah kasus dusta dibawa ke meja mediasi, publik bukan hanya melihat proses hukum; mereka melihat ukuran moral bangsa.
Kita ingat bagaimana filsafat sejak Plato membedakan berbagai jenis dusta. Ada noble lie, dusta yang konon disampaikan demi kebaikan bersama. Ada dusta manipulatif. Ada dusta destruktif. Tetapi kasus ijazah palsu tidak termasuk salah satu dari itu. Ia bukan dusta untuk menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan negara dari perang. Ia adalah dusta untuk memoles citra, mempermudah jalan menuju jabatan, dan kemudian mempertahankan kekuasaan. Tidak ada kemuliaan di sana.
Dalam perspektif Hannah Arendt, kebohongan politik selalu berbahaya bukan hanya karena ia menipu, tetapi karena ia merusak realitas bersama. Masyarakat yang kehilangan realitas bersama akan mudah dibelokkan; mereka tidak lagi mampu membedakan mana sejarah yang benar dan mana yang dikarang. Ketika realitas bersama itu diganggu, yang muncul bukan sekadar kabut ketidakpastian, melainkan erosi kolektif terhadap kemampuan untuk berpikir. Suatu bangsa bisa bertahan tanpa banyak hal, tapi tidak tanpa kemampuan berpikir.
Di sinilah persoalan mediasi terasa janggal. Mediasi mengasumsikan bahwa ada jalan tengah antara “berbohong” dan “tidak berbohong”. Tetapi tidak ada jalan tengah untuk etika. Etika tidak mengenal warna abu-abu ketika yang dipersoalkan adalah kejujuran dasar. Publik yang menuntut penyelidikan bukan sedang menuntut kemenangan politik. Mereka hanya meminta republik kembali ke relnya: bahwa pejabat publik tidak boleh membangun karier di atas klaim palsu. Bahwa seorang pemimpin tidak boleh berdiri di atas ijazah yang tidak pernah ia genggam.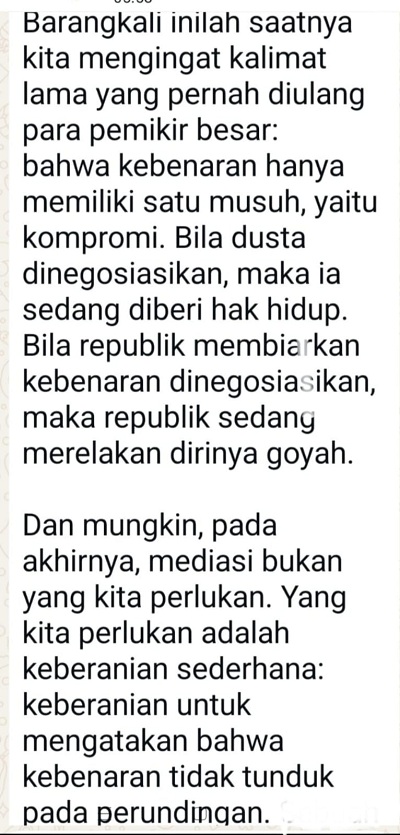
Di beberapa titik sejarah kita melihat bangsa-bangsa memilih integritas dengan harga yang mahal. Di Korea Selatan, seorang presiden mengundurkan diri karena plagiarisme di tesis doktoralnya. Di Jerman, seorang menteri pertahanan kehilangan jabatan karena kutipan yang tidak jujur. Di Jepang, seorang pejabat tinggi mundur hanya karena menerima hadiah kecil yang melanggar etika. Bagi mereka, kejujuran bukan aksesori; ia syarat.
Di Indonesia kita masih mencari bentuk. Kita masih belajar bahwa demokrasi bukan hanya tentang menang pemilu, tetapi tentang memelihara kejujuran dasar yang membuat republik layak dihuni. Kasus ijazah palsu bukan soal dendam politik atau serangan pribadi. Ia adalah cermin yang dipasang di depan kita: apakah kita bangsa yang menoleransi dusta? Apakah kita bangsa yang menganggap integritas sebagai opsi, bukan kewajiban?
Jika kasus ini benar-benar dibawa ke ruang mediasi, maka mediasi itu akan menyimpan risiko: bangsa ini bisa kehilangan kesempatan untuk mengatakan bahwa dusta tidak punya tempat. Bahwa republik ini ingin dibangun di atas kejujuran, bukan kelicikan. Bahwa generasi yang akan datang berhak atas pemerintahan yang tidak takut pada kebenaran.
Barangkali inilah saatnya kita mengingat kalimat lama yang pernah diulang para pemikir besar: bahwa kebenaran hanya memiliki satu musuh, yaitu kompromi. Bila dusta dinegosiasikan, maka ia sedang diberi hak hidup. Bila republik membiarkan kebenaran dinegosiasikan, maka republik sedang merelakan dirinya goyah.
Dan mungkin, pada akhirnya, mediasi bukan yang kita perlukan. Yang kita perlukan adalah keberanian sederhana: keberanian untuk mengatakan bahwa kebenaran tidak tunduk pada perundingan. Sebuah bangsa yang ingin berdiri tegak harus mulai dari sana.
Cimahi, 22 November 2025
EDITOR: REYNA
Related Posts

Komisi Reformasi Polri Dan Bayang-Bayang Listyo Syndrome

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (4): Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional Yang Menyelamatkan Indonesia

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (3): Membangun Stabilitas Politik dan Menghindarkan Indonesia dari Kekacauan Pasca 1965

Negara Yang Terperosok Dalam Jaring Gelap Kekuasaan

Rakyat Setengah Mati, Kekuasaan Setengah Hati

Kolonel (PURN) Sri Radjasa: Jokowo Titip Nama Jaksa Agung, Prabowo Tak Respons

Novel “Imperium Tiga Samudra” (14) – Perang Melawan Asia

Menjaga Dinasti Juara: Menakar Figur Suksesi KONI Surabaya

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (1): Mewarisi Ekonomi Bangkrut, Inflasi 600%

Novel “Imperium Tiga Samudra” (13) – Perang Senyap Mata Uang



No Responses