Penulis : Sri Radjasa
Pemerhati Intelijen
Dalam setiap fase penting demokrasi, publik selalu menaruh harapan bahwa presiden sebagai pemegang mandat tertinggi politik akan mendengar suara rakyat. Namun Keputusan Presiden Prabowo Subianto, Nomor 122/P Tahun 2025, tertanggal 7 November 2025, tentang pengangkatan anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, kembali menghadirkan ironi yang memukul kesadaran kolektif.
Alih-alih merespons tuntutan luas agar Listyo Sigit Prabowo diberhentikan sebagai Kapolri setelah rangkaian kontroversi yang menurunkan kepercayaan publik, keputusan itu justru menempatkan Sigit sebagai anggota komisi yang berfungsi menata ulang institusi tempat ia sendiri dipersoalkan. Dalam perspektif etika pemerintahan modern, langkah ini bertentangan dengan prinsip conflict of interest, tetapi lebih dari itu, bertentangan dengan “filsafat akal sehat”, sebuah pijakan moral universal yang menjadi fondasi penilaian praktis dalam tradisi filsafat Barat sejak Thomas Reid hingga tradisi Common Sense Realism di era modern.
Kekecewaan publik itu tidak berhenti sebagai desas-desus di ranah media sosial. Ia menjelma menjadi peristiwa politik yang terang benderang ketika sejumlah tokoh masyarakat melakukan walk out dalam audiensi Komisi Reformasi Polri. Roy Suryo dan beberapa tokoh lain dilarang hadir karena berstatus tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, sebuah perkara yang sejak awal dianggap banyak pihak sarat kepentingan politik. Penjelasan Jimly Asshiddiqie yang disampaikan kemudian justru menjadi paradoks, dimana Komisi Reformasi Polri yang katanya, bukan forum untuk mendengar kasus per kasus, dan “tidak etis” menghadirkan seorang tersangka di hadapan komisi serta jajaran jenderal yang ikut menghadiri forum tersebut. Pernyataan itu seolah menegaskan jarak antara gagasan reformasi institusi dan realitas politik yang melingkupinya.
Di sinilah persoalan intelektual dan moralitas seorang ilmuwan publik dipertaruhkan. Jimly sebelumnya menyatakan secara terbuka bahwa kasus Roy Suryo CS secara hukum tidak layak dibawa ke meja persidangan, tetapi pada saat bersamaan ia menolak kehadiran pihak yang menurut pandangannya sendiri belum pantas disidangkan. Jika dalam tradisi rule of law seseorang dianggap tidak bersalah sampai diputuskan pengadilan, maka penolakan tersebut tidak hanya meruntuhkan asas itu, tetapi juga menunjukkan keretakan antara nalar akademik dan praktik politik. Dalam konteks inilah muncul pertanyaan publik, apakah Komisi Reformasi Polri dibentuk untuk menampung keluhan masyarakat atau sekadar menjadi panggung formalitas tanpa keberanian menyentuh akar masalah?
Logika reformasi selalu bertumpu pada kemampuan mengurai patologi institusi, dan dalam konteks Polri, patologi itu terpantul jelas melalui kasus-kasus yang ditangani aparat. Persoalan kriminalisasi tokoh publik, dugaan rekayasa kasus, atau penyalahgunaan kewenangan adalah data empiris yang seharusnya menjadi bahan baku reformasi. Jika komisi menolak mendengar kasus yang menjadi representasi dari persoalan struktural Polri, lalu dari mana reformasi itu dimulai?
Literatur tentang reformasi sektor keamanan yang ditulis oleh ahli seperti David Bayley dan Andrew Goldsmith menegaskan bahwa lembaga pengawasan tidak boleh steril dari keluhan masyarakat, justru sebaliknya, suara korban adalah muatan utama penyusunan agenda reformasi.
Menutup pintu bagi suara publik berarti memutus aliran informasi primer yang diperlukan untuk merombak kultur, struktur, dan tata kelola institusi kepolisian.
Karena itu, fenomena ini menunjukkan apa yang oleh penulis sebut sebagai Listyo Syndrome. Sebuah kondisi ketika lingkaran kekuasaan dan elite intelektual yang berada di orbitnya mulai melihat persoalan dari kaca mata sang penguasa institusi, bukan dari perspektif masyarakat.
Dalam psikologi politik, kondisi seperti ini dikenal sebagai institutional capture, dimana ketika aktor-aktor independen justru terserap ke dalam cara pandang birokrasi yang seharusnya mereka kritik. Dalam berbagai studi tentang hubungan sipil-polisi, hal ini biasanya disertai dengan proses normalisasi, yakni ketika perilaku, sikap, dan cara berpikir yang bermasalah perlahan dianggap lumrah. Apalagi ketika kekuasaan politik memberi ruang bagi kondisi itu untuk terus berlangsung.
Listyo Sigit memang telah lama menjadi simbol polarisasi dalam tubuh Polri. Di satu sisi dipertahankan oleh pusat kekuasaan, di sisi lain menjadi sorotan publik karena rentetan kasus yang muncul di era kepemimpinannya. Namun bertahannya ia di posisi strategis, bahkan kini sebagai bagian dari Komisi Reformasi Polri, memperlihatkan bahwa reformasi kepolisian belum benar-benar dipahami sebagai kebutuhan sistemik, melainkan masih menjadi komoditas politik. Listyo Syndrome pada akhirnya bukan hanya soal satu nama, melainkan tentang bagaimana struktur kekuasaan gagal memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan institusi.
Di tengah situasi ini, masyarakat kembali merasakan jarak antara jargon reformasi dan praksis. Dalam pengalaman sejarah Indonesia, setiap kali agenda reformasi dipisahkan dari keberanian moral, ia berhenti sebagai deretan dokumen dan rapat tanpa perubahan berarti.
Kajian lembaga-lembaga internasional seperti UNODC dan International Crisis Group menunjukkan bahwa negara-negara dengan kepolisian yang berhasil direformasi, seperti Georgia pada awal 2000-an atau Afrika Selatan pasca apartheid, menjadikan keberanian melawan status quo sebagai elemen utama. Reformasi bukan pekerjaan administrasi, melainkan tindakan politik yang menantang kenyamanan kelompok elit.
Di Indonesia, jejak kekecewaan ini semakin kuat ketika publik melihat bagaimana ruang-ruang partisipasi kerap dipersempit. Pembatasan kehadiran Roy Suryo CS hanya mempertegas bahwa suara kritis tetap dianggap gangguan, bukan bahan refleksi. Padahal demokrasi bertumpu pada kemampuan negara mendengar suara paling kecil sekalipun. Mengutip John Dewey, demokrasi adalah “metode komunikasi,” bukan sekadar struktur kekuasaan. Bila komunikasi diputus, demokrasi runtuh ke dalam formalitas belaka.
Karena itulah, publik memandang keputusan Presiden Prabowo bukan sekadar kontroversi administratif, tetapi sebagai penanda arah politik negara. Di tengah tuntutan agar kepolisian lebih profesional, transparan, dan bebas dari tekanan politik, masuknya figur yang sedang dipersoalkan justru melemahkan legitimasi komisi itu sendiri.
Narasi besar reformasi Polri tidak dapat dibangun dengan fondasi yang rapuh. Bahkan dalam logika kepemimpinan modern, integritas lembaga jauh lebih penting daripada nama besar yang dipertahankan.
Harapan rakyat untuk memiliki polisi yang mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum secara adil mungkin sedang berada dalam masa menunggu yang panjang. Namun kesabaran publik juga memiliki batas, sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah berbagai negara. Ketika ruang formal tak lagi memadai, masyarakat menemukan cara lain untuk menyampaikan aspirasi. Sinyal itu tampaknya mulai muncul kembali, bahwa demokrasi tidak boleh dibiarkan berjalan di rel yang dibelokkan oleh segelintir elite.
Reformasi Polri, bila ingin kembali pada jalur akal sehat, harus berangkat dari keberanian mendengar suara rakyat, bukan dari loyalitas kepada figur lama yang terus dirawat oleh sindrom kekuasaan.
EDITOR: REYNA
Tags:Related Posts

Ira Harus Bebas Demi Hukum: Suara Ferry Irwandi yang Mengguncang Logika Penegakan Korupsi

Thrifting: Fenomena Baru Yang Kini Jadi Sorotan DPR dan Menteri Keuangan

Dusta Yang Ingin Dimediasi

Sri Radjasa: Reformasi Polri Setengah hati, Sekadar Perbaikan Kosmetik

Modus Ala Jokowi

Trump: “Bukan Masalah Pertanyaanmu, Tapi Sikapmu, Kamu Adalah Wartawan Yang Parah”

Teguran Presiden di Ruang Tertutup: Mahfud MD Ungkap Instruksi Keras kepada Kapolri dan Panglima TNI

Orang Jawa Sebagai “Bani Jawi” Adalah Keturunan Nabi Ismail: Perspektif Prof. Menachem Ali

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (4): Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional Yang Menyelamatkan Indonesia

Novel “Imperium Tiga Samudara” (15) – Operation Floodgate

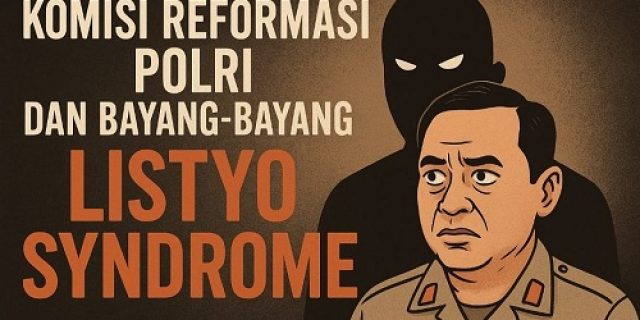

No Responses