Oleh: Radhar Tribaskoro
Istilah mikul duwur, mendem jero kembali bergema dalam ruang politik kita. Ia bukan kata baru. Ia pernah terucap di suatu masa yang jauh, ketika Soekarno—yang tengah menanggung beban sejarah dan tubuh yang mulai rapuh—bertanya kepada Soeharto, “Aku mau kamu apakan, Harto?” Jawaban Soeharto waktu itu meredakan banyak ketakutan. Rakyat masih melihat Soekarno sebagai Bapak bangsa; janganlah luka politik ditambah dengan penghinaan. Ada rasa kemanusiaan yang ingin dijaga. Ada hormat yang ingin tetap utuh.
Tetapi ketika Presiden Prabowo mengucapkan kalimat yang sama, suasananya berbeda. Ia menyampaikannya di tengah sorotan publik terhadap proyek kereta cepat Whoosh. Masyarakat, atau sedikitnya Danantara, menyambut baik kesediaan negara menanggung kerugian Whoosh. Tetapi sambutan itu tidak serta-merta berarti bahwa publik bersedia melihat kesalahan masa lalu dikubur di balik dalih penghormatan. Di titik inilah makna pepatah itu bergeser: apakah ia sedang menjaga martabat atau justru sedang menutup pintu pemeriksaan?
Keresahan itu belum sempat dirumuskan dalam kata-kata ketika sehari setelahnya, Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan delapan aktivis sebagai tersangka, atas laporan presiden sebelumnya. Gumam di warung kopi berubah menjadi senyap yang berat. Seolah ada sesuatu yang bergerak diam-diam: sebuah pola, sebuah kelanjutan, sebuah penyingkapan.
Maka, pidato itu bukan sekadar pidato. Ia membawa implikasi yang berlapis. Untuk memahaminya, kita perlu menengok bukan hanya isinya, tetapi narasi yang menggerakkannya. Apa makna mikul duwur, mendem jero ketika ia berpindah dari bahasa keluarga ke bahasa negara? Apa yang terjadi ketika etika rasa hormat itu dibawa masuk ke ruang kebijakan publik, hukum, dan institusi?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membawa kita pada inti pembahasan.
***
Dalam bahasa Jawa, “mikul duwur, mendem jero” adalah ungkapan yang lembut tetapi tegas. Ia mengajarkan agar kita menghormati orang yang pernah berjasa, mengangkat tinggi martabatnya di hadapan publik, sekaligus menyimpan rapat kesalahan atau kelemahannya. Pepatah ini lahir dari dunia batin masyarakat agraris yang menempatkan hubungan manusia sebagai dasar dunia sosial: guru, orang tua, patron politik, pemuka desa, adalah sumber kehidupan. Hidup bergulir dalam jaringan balas budi. Dalam jaringan itu, yang paling tinggi nilainya adalah kesetiaan.
Dalam konteks rumah, keluarga, komunitas kecil, pepatah ini tetap merupakan cahaya. Ia mengajarkan kerendahan hati, rasa hormat, kesadaran bahwa manusia tidak pernah berdiri sendiri. Tetapi ketika pepatah ini melangkah keluar dari serambi rumah dan masuk ke ruang publik, ia berubah. Logika personal yang lembut itu berjumpa dengan hukum, kebijakan, administrasi, dan negara yang menuntut keteraturan impersonal. Di sinilah ketegangan itu muncul.
Filsafat Timur—termasuk Jawa, Cina, dan Jepang—banyak dibangun di atas etika relasional. Konfusius menyebutnya ren, kemanusiaan yang bertumbuh dalam hubungan. Etika tidak lahir dari prinsip abstrak, tetapi dari praktik kesetiaan pada hubungan guru-murid, ayah-anak, penguasa-rakyat. Di Jepang, konsep giri (kewajiban moral karena hubungan) dan on (hutang budi) memberi struktur bagi cara orang hidup. Di Jawa, andhap asor dan tepa slira memberi ritme pada sopan santun, sementara mikul duwur, mendem jero menjadi penanda tertinggi penghormatan terhadap patron.
Sebaliknya, tradisi filsafat modern Barat—setidaknya sejak Immanuel Kant—berdiri di atas etika impersonal. Hukum moral tidak boleh tunduk pada hubungan personal. Ada prinsip universal: jika sesuatu benar, ia harus benar untuk semua, tanpa memandang siapa pelakunya. Negarapun harus beroperasi dengan logika yang sama. Negara modern, kata Max Weber, dibangun di atas rasionalitas legal, bukan karisma pribadi atau hubungan patronase. Hukum mengikat bukan karena siapa yang mengatakan, tetapi karena keabsahan prosedurnya.
Di sinilah persoalannya: ketika nilai privat seperti “mikul duwur, mendem jero” dipakai sebagai dasar kebijakan publik, maka negara mulai bergerak mundur ke arah “pemerintahan keluarga” atau household politics. Pemimpin bukan lagi pelayan publik, tetapi kepala keluarga. Rakyat bukan warga negara, tetapi anak yang harus patuh. Dalam sistem seperti itu, kesalahan tidak boleh dibuka, pengadilan berubah menjadi urusan keluarga, dan kritik dilihat bukan sebagai fungsi demokrasi, melainkan sebagai bentuk durhaka.
Kita pernah menyaksikan contoh-contoh ini. Di Orde Baru, loyalitas personal kepada Presiden Soeharto mengatur seluruh alur kebijakan. Orang-orang yang pernah berjasa kepada penguasa diberi ruang, dilindungi, dan ditopang. Kesalahan mereka tidak boleh menjadi urusan publik. Korupsi, meski dikenali, dianggap “urusan internal keluarga besar negara”. Yang mengancam bukan pelanggaran hukum, tetapi “ketidaksetiaan”. Sistem feodal yang berkelindan dengan birokrasi modern inilah yang merusak demokrasi Indonesia sebelum 1998.
Di Rusia, Vladimir Putin mempraktikkan bentuk modern dari mikul duwur, mendem jero. Jaringan loyalis yang lahir dari lingkaran KGB dan pemerintahan St. Petersburg menjadi tulang punggung kekuasaan. Selama setia, kesalahan tidak dibuka. Tetapi kejatuhan Boris Yeltsin memperlihatkan paradoksnya: ketika “balas budi” menjadi sistem negara, kekuasaan bertahan bukan karena legitimasi, tetapi karena keterikatan personal yang saling menyandera. Pemerintahan berubah menjadi ikatan utang yang tidak pernah selesai.
Di Cina kontemporer, ada prinsip yang mirip dalam bentuk shou en—menjaga utang budi. Tetapi Partai Komunis Cina melakukan langkah yang berbeda sejak era Deng Xiaoping. Mereka memahami bahaya loyalitas personal terhadap keutuhan negara. Maka, dibangunlah sistem disiplin internal yang keras: sekalipun seseorang berjasa besar, bila ia korup, ia harus jatuh. Sejumlah tokoh besar Partai—Bo Xilai, Zhou Yongkang, dan banyak lainnya—ditahan atau dieksekusi politik bukan karena mereka tidak berjasa, tetapi karena kesalahan mereka tidak boleh dianggap sebagai aib pribadi yang harus ditutupi. Inilah etika impersonal dalam bentuk otoriter, yang tentu problematik dari sudut demokrasi, tetapi tetap menjadi contoh bahwa negara tidak dapat berdiri di atas logika balas budi personal.
Maka persoalannya bukan pada pepatahnya. Pepatah itu baik, namun ia adalah etika privat, bukan etika publik. Yang membahayakan adalah ketika sebuah negara lupa membedakan wilayah antara keduanya. Di banyak tempat di dunia, termasuk Indonesia, kebingungan ini masih berlangsung. Nilai-nilai keluarga dibawa ke panggung bernegara. Kecintaan pribadi dianggap sebagai dasar kebijakan. Lalu hukum menjadi lentur mengikuti kedekatan.
Bagaimana suatu negara bisa keluar dari etika personal menuju etika impersonal?
Proses ini memerlukan tiga hal. Pertama, pendidikan publik mengenai batas antara ranah personal dan ranah institusional. Ini bukan sekadar soal UU, tetapi soal budaya politik. Demokrasi menuntut keberanian untuk memisahkan rasa hormat sebagai anak atau murid dari penilaian sebagai warga negara. Kedua, pembentukan institusi yang kuat dan konsisten. Lembaga penegak hukum hanya dapat dipercaya bila ia tidak menjadi perpanjangan tangan keluarga politik. Ketiga, pembiasaan praktik akuntabilitas: pejabat yang bersalah harus diperiksa, bukan dilindungi atas nama jasa masa lalu.
Negara-negara Skandinavia mencapai etika impersonal bukan karena mereka lebih rasional dari bangsa lain, tetapi karena mereka berjuang melalui pergulatan panjang untuk memisahkan kepentingan publik dari jaringan keluarga aristokrat. Jepang pun berhasil keluar dari feodalisme bukan dengan menghapus rasa hormat, tetapi dengan menggantikannya menjadi loyalitas pada peran, bukan pada pribadi.
Negara demokratis tidak pernah meminta kita berhenti menghormati orang yang berjasa. Ia hanya meminta agar penghormatan itu tidak menggantikan keadilan. Kita boleh menyimpan kesalahan keluarga di ruang privat. Tetapi ketika kesalahan itu menyangkut kekuasaan, uang publik, keselamatan rakyat, dan masa depan negara, maka ia menjadi urusan bersama.
“Mikul duwur, mendem jero” tetap indah bila ia tinggal di dalam rumah. Tetapi dalam negara, yang kita perlukan bukan kesetiaan pada orang, melainkan kesetiaan pada prinsip.
Karena bangsa hanya dapat berdiri tegak bila kehormatan tidak diberikan kepada mereka yang berjasa semata, tetapi kepada mereka yang bertanggung jawab.
Menara Unas, 8 November 2025
EDITOR: REYNA
Related Posts

Jejak Dua Tokoh Nasional di Era SBY, Diduga Menitip MRC ke Mantan Dirut Pertamina

Presiden Harus Belajar dari Sultan Iskandar Muda

Mencuri Uang Rakyat Turun-Temurun

Pangan, Martabat, dan Peradaban: Membaca Kedaulatan dari Perspektif Kebudayaan

Prabowo Whoosh Wus

Jebakan Maut Untuk Presiden

Novel “Imperium Tiga Samudra” (9) – Prometheus

Ribut Soal Pahlawan, Habib Umar Alhamid: Soeharto Layak dan Pantas Jadi Pahlawan Nasional

Sri Radjasa Chandara Buka Suara: Ada Tekanan Politik di Balik Isu Pergantian Jaksa Agung

Chris Komari: Kegiatan Yang Dilindungi Konstitusi Adalah Hak Konstitusional Yang Tidak Dapat Dipidana Dan Dikriminalisasi


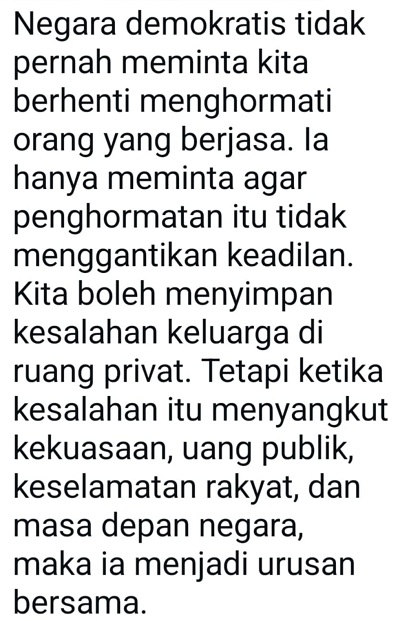

No Responses